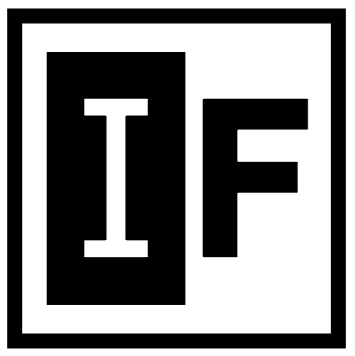IndonesianForecast, JAKARTA — Meski Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10/2025 yang seharusnya mengatur peta jalan pengakhiran operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk mencapai target net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat, namun pelaksanaannya belum menunjukkan progres konkret.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah belum ada tindak lanjut komitmen dalam mendukung pensiun PLTU termasuk PLTU Cirebon-1 sebesar 660 MW. Di sisi lain, terdapat wacana PLN akan membatalkan pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena biaya penalti yang harus dibayarkan selama lima tahun dinilai terlalu besar mencapai sekitar Rp60 triliun.
Fabby menilai keputusan PLN dilandasi oleh ketidakpastian akibat persetujuan tidak kunjung diberikan oleh pemerintah. Rencana pensiun dini PLTU Cirebonn-1 dimulai di 2021 saat Indonesia menjadi bagian dari Energy Transition Mechanism (ETM) yang diluncurkan ADB bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Conference of Parties (COP26) di Glasgow.
Rencana tersebut dilanjutkan saat Indonesia menjadi Presiden G20 dan menyepakati Just Energy Transition Partnership (JETP) di tahun yang sama. Rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 telah melalui proses kajian kelayakan teknis dan ekonomis, dan sejumlah kesepakatan antara PLN dan PT Cirebon Electric Power. Asian Development Bank (ADB) juga telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk pensiun dini ini, tetapi masih dinilai belum memadai oleh pemerintah Indonesia.
“Apabila pemerintah tidak segera memfinalkan keputusan pensiun PLTU Cirebon, maka akan mengurangi kredibilitas negara dan memperburuk iklim investasi di Indonesia, karena langkah tersebut tidak selaras dengan komitmen yang dibuat Indonesia sendiri,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (4/12/2025).
Selain itu, pembatalan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan memperlambat transisi energi menuju dekarbonisasi di sektor kelistrikan. Hal ini bertentangan dengan tujuan Presiden Prabowo yang ingin meninggalkan energi fosil sepuluh tahun dari sekarang, sebagaimana disampaikan pada pidato kenegaraan di DPR pada 15 Agustus 2025 lalu.
Menurut Febby, keengganan pemerintah dan PLN untuk mewujudkan pensiun dini PLTU batu bara menunjukkan kemunduran komitmen transisi energi. Adanya kekhawatiran terhadap biaya pensiun dini yang dianggap tinggi hanya melihat dari biaya kompensasi kontrak belaka dan tidak mempertimbangkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari penurunan biaya polusi dan kesehatan publik. Selain itu, biaya yang tinggi tersebut muncul karena kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri, yang hingga kini enggan dikoreksi.
Kajian yang dilakukan IESR menunjukkan bahwa pensiun dini PLTU sebelum 2050 justru memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang dibandingkan membiarkan PLTU beroperasi hingga usia pensiun alami.
“Secara umum, biaya pensiun dini PLTU menjadi mahal karena struktur Purchase Power Agreement(PPA) PLTU di mana terdapat klausul take or pay (TOP) yang membuat PLN harus membayar listrik pada tingkat kapasitas dan tinggi dan kontrak PPA selama 30 tahun, tiga kali dari waktu normal pengembalian investasi (payback period). Selain itu kebijakan domestic market obligation untuk batubara, membuat risiko harga bahan bakar ditanggung oleh PLN dan negara sehingga seolah-olah biaya pembangkitan listrik PLTU murah. Kebijakan ini juga membuat pembangkit energi terbarukan tidak dapat berkompetisi secara adil,” tuturnya.
Fabby menambahkan listrik dari PLTU sejatinya tidak murah karena ada eksternalitas yang tidak pernah dihitung, yaitu dampak kesehatan dan biaya akibat polusi udara yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah dalam bentuk kenaikan beban BPJS.
Dalam kajian IESR menemukan manfaat pensiun dini PLTU ditinjau dari penghematan subsidi, penurunan risiko dan biaya kesehatan, justru 2 hingga 4 kali lebih besar dibandingkan biaya pensiun dini itu sendiri.
Studi IESR di tahun 2022 memperkirakan biaya pensiun dini PLTU di sistem PLN yang sesuai dengan target Persetujuan Paris, yaitu 9,2 GW di 2030 memerlukan biaya mencapai US$4,6 miliar atau setara Rp73,6 triliun. Nilainya akan meningkat menjadi US$27,5 miliar atau setara Rp440 triliun untuk mempensiunkan PLTU sisanya hingga 2045.
Namun, potensi penghematan yang diperoleh jauh lebih besar. Subsidi listrik batu bara yang dapat dihindari diperkirakan mencapai US$34,8 miliar atau Rp556 triliun, sementara penghematan biaya kesehatan publik mencapai US$61,3 miliar atau Rp980 triliun pada periode yang sama.
Selain itu, kebutuhan investasi energi terbarukan, jaringan listrik dan penyimpan energi untuk menggantikan energi dari pengakhiran operasi PLTU dan memenuhi penambahan permintaan tenaga listrik baru sekitar US$1,2 triliun hingga US$1,3 triliun hingga 2050. Namun yang perlu dicatat bahwa biaya tersebut sesungguhnya merupakan investasi kelistrikan, tidak dinikmati oleh pemilik aset dan aset seluruh infrastruktur tersebut akan menjadi aset PLN dan negara di masa depan.
“Keputusan pembatalan pensiun dini PLTU Cirebon I, akan menjadi pionir bagi percepatan penghentian PLTU lainnya di Indonesia dengan menggunakan skema ETM atau blended finance, dan memperkuat transisi energi hijau di Indonesia,” ucap Febby.
Sementara itu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu menuturkan pemerintah seharusnya tidak hanya menunggu pendanaan dari luar tetapi juga berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang progresif untuk mendorong pensiun dini PLTU Batubara.
Hal ini termasuk mengalihkan subsidi energi fosil ke energi bersih, memperketat standar emisi bagi PLTU, mempercepat reformasi di sektor kelistrikan agar lebih kompetitif bagi energi terbarukan, dan memastikan transisi energi yang adil bagi masyarakat terdampak.
“Jika pemerintah serius dengan transisi energi, maka seharusnya anggaran negara dan kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, bukan terus memberi subsidi pada batu bara,” ujarnya.